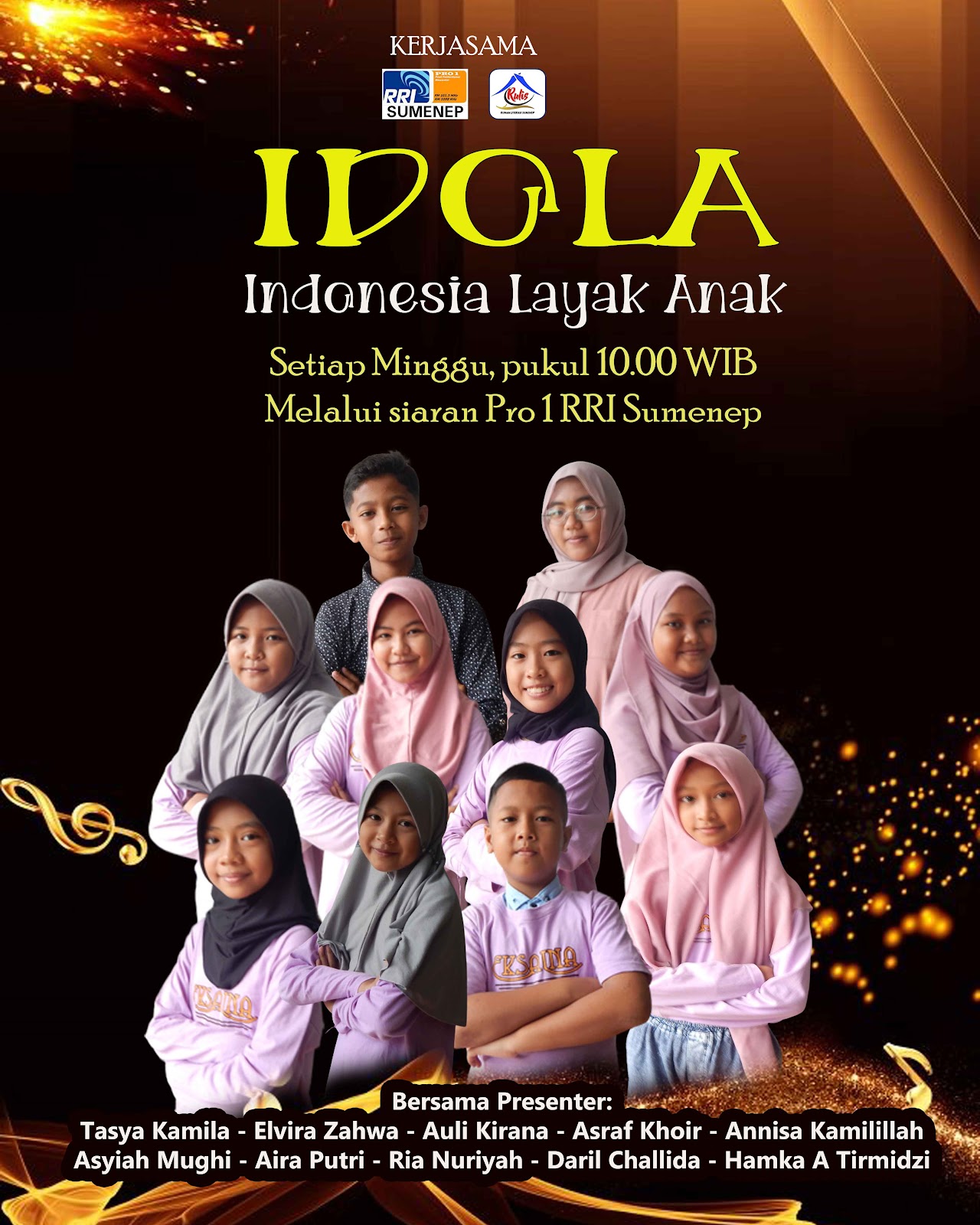Komunitas Lokal Sebagai Aktor
Syaf Anton Wr Komunitas masyarakat pesisir Legung, Sumenep Kehidupan yang harmoni menjadi penekanan kehidupan yang diharapkan dalam r...
http://www.rumahliterasisumenep.org/2018/04/komunitas-lokal-sebagai-aktor.html
Syaf Anton Wr
Kehidupan yang harmoni menjadi penekanan kehidupan yang diharapkan dalam rampa’ naong beringin korong, serta ghu’tegghu’ sabbhu’ atau song-osong lombhung, merupakan solidaritas sosial antar warga. Meski kekerasan kerap menjadi indentitas orang Madura seperti carok misal, dalam pandangan orang Madura memiliki tempat tersendiri, karena alasan-alasan tertentu karena perasaan malo akibat harga diinjak-injak sehingga melahirkan carok. Ango’ potea tolang etembhang pote mata atau otang pesse nyerra pesse, otang rassa nyerra rassa, otang nyaba nyerra nyaba yang barangkali menjadi pertimbangan mereka. Sebenarnya semua itu dapat diselesaikan dengan terhormat bila diawali dengan bhak-rembhak yang sebenarnya mengakar kuat dalam masyarakat Madura.
Contoh diatas merupakan bagian kecil dari pendidikan karakter masyarakat melalui kearifan lokal, yang seharusnya telah dikenal dan atau diperkenalkan dari generasi ke generasi. Karena pada dasarnya kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal berupa tradisi, petatah-petitih dan semboyan hidup.
Istilah pemberdayaan mungkin mengesankan bahwa komunitas Madura sekarang dalam keadaan tidak berdaya atau terpuruk. Istilah ini melukiskan keadaan yang negatif dan ada yang ingin diubah. Untuk mengubahnya, pertama dan terpenting adalah komunitas itu sendiri sebagai faktor intern pemberdayaan. Pemerintah, komunitas masyarakat, baik didalam maupun dari luar atau siapapun tidak bisa menggantikan peranan komunitas itu sebagai aktor pemberdayaan.
Karena pemberdayaan (kemudian pembangunan) yang bergulir bukanlah buah derma (hadiah). Jauh sebelumnya, kebiasaan masyarakat yang kemudian menjadi tradisi, semangat mandiri, berprakarsa, dan semangat gotong royong (song-osong lombung) ini sangat kuat di kalangan masyarakat Madura. Membangun sebuah rumah, pemilik tidak repot lagi mencari tukang bangunan, material, dan bahkan suguhan, para tetangga dan kerabat keluarga tanpa pretensi apapun telah mempersiapkan segalanya. Demikian pula aktifitas-aktifitas lainnya, yang semuanya mengarah pada kekuatan dasar masyarakat, yang mandiri, yang madani.
Menghidupkan kembali ingatan kolektif terhadap hal tersebut salah satu metode melalui pendekatan budaya merupakan usaha yang signifikan. Melalui dialog budaya, yaitu bagaimana mengembalikan suku, etnik dan masyarakat Madura, kembali menjadi komunitas-komunitas lokal, menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang luhur. Untuk itu, pendidikan pembebasan melalui proses penyadaran akan menjadi kunci dan bisa dilakukan melalui pemaduan usaha-usaha produktif guna menjawab persoalan hari-hari yang kongkrit, dengan tanpa melupakan, bahwa usaha produktif ini merupakan bagian integral dari proses penyadaran dan pembebasan diri komunitas dari jebakan-jebakan globalisasi budaya.
Penyadaran diri tidak cukup hanya dengan mempersoalkan dan memperbincangkan semata, tapi bagaimana membangun jati diri masyarakat dan mengaktulisasikan dalam realitas kehidupan nyata. Sebab kenyataan yang terjadi, fungsi dan peran masyarakat dalam artian membentuk kekuatan budaya telah dieksploitasi oleh kecenderungan yang bersifat material, sementara budaya (daerah, lokal dan tradisional) yang lebih mengacu pada konsep kehidupan bersama, tenggang rasa dan gotong royong itu, hampir kehilangan maknanya. Bila fungsi tersebut lumpuh, apa yang diharapkan dari gerakan kekuatan budaya Madura sendiri?, kecuali secara lambat laun masyarakat Madura akan kehilangan budaya Maduranya.
Bersambung:
 |
| Komunitas masyarakat pesisir Legung, Sumenep |
Contoh diatas merupakan bagian kecil dari pendidikan karakter masyarakat melalui kearifan lokal, yang seharusnya telah dikenal dan atau diperkenalkan dari generasi ke generasi. Karena pada dasarnya kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal berupa tradisi, petatah-petitih dan semboyan hidup.
Istilah pemberdayaan mungkin mengesankan bahwa komunitas Madura sekarang dalam keadaan tidak berdaya atau terpuruk. Istilah ini melukiskan keadaan yang negatif dan ada yang ingin diubah. Untuk mengubahnya, pertama dan terpenting adalah komunitas itu sendiri sebagai faktor intern pemberdayaan. Pemerintah, komunitas masyarakat, baik didalam maupun dari luar atau siapapun tidak bisa menggantikan peranan komunitas itu sebagai aktor pemberdayaan.
Karena pemberdayaan (kemudian pembangunan) yang bergulir bukanlah buah derma (hadiah). Jauh sebelumnya, kebiasaan masyarakat yang kemudian menjadi tradisi, semangat mandiri, berprakarsa, dan semangat gotong royong (song-osong lombung) ini sangat kuat di kalangan masyarakat Madura. Membangun sebuah rumah, pemilik tidak repot lagi mencari tukang bangunan, material, dan bahkan suguhan, para tetangga dan kerabat keluarga tanpa pretensi apapun telah mempersiapkan segalanya. Demikian pula aktifitas-aktifitas lainnya, yang semuanya mengarah pada kekuatan dasar masyarakat, yang mandiri, yang madani.
Menghidupkan kembali ingatan kolektif terhadap hal tersebut salah satu metode melalui pendekatan budaya merupakan usaha yang signifikan. Melalui dialog budaya, yaitu bagaimana mengembalikan suku, etnik dan masyarakat Madura, kembali menjadi komunitas-komunitas lokal, menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang luhur. Untuk itu, pendidikan pembebasan melalui proses penyadaran akan menjadi kunci dan bisa dilakukan melalui pemaduan usaha-usaha produktif guna menjawab persoalan hari-hari yang kongkrit, dengan tanpa melupakan, bahwa usaha produktif ini merupakan bagian integral dari proses penyadaran dan pembebasan diri komunitas dari jebakan-jebakan globalisasi budaya.
Penyadaran diri tidak cukup hanya dengan mempersoalkan dan memperbincangkan semata, tapi bagaimana membangun jati diri masyarakat dan mengaktulisasikan dalam realitas kehidupan nyata. Sebab kenyataan yang terjadi, fungsi dan peran masyarakat dalam artian membentuk kekuatan budaya telah dieksploitasi oleh kecenderungan yang bersifat material, sementara budaya (daerah, lokal dan tradisional) yang lebih mengacu pada konsep kehidupan bersama, tenggang rasa dan gotong royong itu, hampir kehilangan maknanya. Bila fungsi tersebut lumpuh, apa yang diharapkan dari gerakan kekuatan budaya Madura sendiri?, kecuali secara lambat laun masyarakat Madura akan kehilangan budaya Maduranya.
Bersambung:
- Budaya Madura di Persimpangan Jalan?
- Potret Budaya Sebagai Jati Diri Masyarakat Madura
- Revitalisasi Budaya Lokal, Menjawab Tantangan Jaman
- Komunitas Lokal Sebagai Aktor
Disampaikan pada Seminar Regional Kontoversi Provinsi Madura, Ponpes Annuqayah, Sumenep, April 2016